Curhat dari Laki-Laki yang Lelah Ditanya “Kapan Nyusul?”
Kalau hidup ini sinetron, maka saya bukan pemeran utama. Saya cuma figuran yang selalu ada di nikahan teman, bawa amplop, lalu difoto sendirian di pojok pelaminan. Setiap kondangan, saya tidak hanya menyumbang doa, tapi juga menyumbang kesabaran mendengar kalimat klasik, “Kapan nyusul?”
Saya belum menikah, bukan karena saya tidak laku. Tapi karena hidup belum kasih kesempatan. Pekerjaan tetap belum datang, Tabungan pun masih bentuk harapan, Mau ngajak anak orang serius, tapi saya sadar dia butuh masa depan, bukan cuma cinta dan motor matic yang angsurannya masih jalan.
Di titik ini, saya mulai merasa hidup ini seperti kurikulum yang terlalu cepat. Orang lain sudah sampai bab “pernikahan & parenting”, saya masih tertahan di “mencari kerja yang sesuai passion, tapi realistis.” Kadang saya iri, kadang saya sedih. Tapi lebih sering saya bingung: apakah ini ujian atau saya cuma lagi apes?
Saat Tuhan Jadi Tempat Ngadu Soal Jodoh dan Pekerjaan
Di tengah krisis ini, saya mulai lebih sering shalat malam. Bukan karena ingin jadi wali, tapi karena malam-malam adalah waktu paling jujur untuk nangis tanpa malu. Saya mengadu pada Tuhan, bukan minta diberi pasangan kaya dan cantik, tapi sekadar seseorang yang bisa diajak ngobrol dan tidak pergi setelah tahu isi rekening saya.
Katanya, kalau kita dekat dengan Allah, maka jodoh dan rezeki akan ikut datang. Saya sudah dekat, sudah berdoa, sudah sabar. Tapi undangan nikah tetap datangnya dari orang lain. Di titik itu, saya mulai bertanya: mungkin ini bukan tentang doa saya yang kurang kuat, tapi tentang proses saya yang memang harus lebih panjang.
Spiritual well-being—kesejahteraan spiritual—mulai terasa penting. Saya bukan cuma butuh uang dan pasangan, saya butuh rasa bahwa hidup ini ada maknanya. Gomez & Fisher (2003) bilang, spiritualitas itu tentang merasa hidup kita diarahkan oleh sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau tiap malam arah hidup saya cuma ke pojok kamar buat mbatin, saya jadi ragu Tuhan beneran lihat saya nggak, sih?
Lelaki, Iman, dan Pertanyaan “Kenapa Belum Nikah?”
Sebagai laki-laki, ekspektasi datang bertubi-tubi. Harus kerja mapan, harus bisa biayai pernikahan, harus siap jadi imam. Padahal kadang saya masih bingung, bacaan doa Qunut aja suka ketuker. Tapi tetap saja, orang-orang menganggap saya harus “siap nikah” hanya karena umur saya udah lewat kepala dua.
Di tengah semua tekanan itu, spiritualitas bukan pelarian, tapi tempat pulang. Saya percaya, Tuhan tidak menilai saya dari apakah saya sudah menikah atau belum, tapi dari apakah saya tetap bertahan dalam niat baik meski dunia belum memihak. Saya belajar untuk tidak buru-buru. Karena menikah tanpa kesiapan bukan ibadah, tapi bisa jadi bencana kolektif.
Tenang, Tuhan Nggak Cuma Sayang yang Udah Nikah
Kadang saya iri lihat pasangan muda yang mesra di story. Tapi lalu saya ingat: hidup bukan tentang siapa cepat dia dapat. Tapi siapa yang sabar sampai saatnya tepat. Saya nggak ingin menikah hanya untuk sekadar “tidak sendirian.” Saya ingin menikah ketika saya bisa jadi teman hidup yang utuh—bukan yang setengah lelah, setengah nekat.
Kalau kamu laki-laki, belum nikah, dan sedang bertanya-tanya kenapa hidupmu terasa seperti skripsi yang tak kunjung revisi, saya cuma mau bilang: kamu tidak sendirian. Banyak dari kita sedang berjuang di balik senyum sabtu malam yang pura-pura bahagia. Kita bukan gagal, kita cuma belum waktunya.
Dan ingat, Tuhan tidak hanya sayang mereka yang sudah posting foto pre-wedding. Tuhan juga dengar doa-doa kamu di malam minggu yang sunyi. Doa dari pemuda yang belum bisa beli cincin, tapi tetap menjaga niat baiknya. Mungkin itu lebih mulia dari pernikahan instan yang lahir dari panik, bukan dari yakin.*
[*] ditulis oleh laki-laki yang belum menikah dan banyak gabutnya.





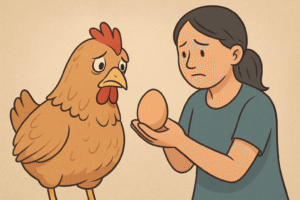


Leave a Comment